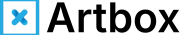## Polemik Penonaktifan Gubernur Aceh Abdullah Puteh: Pertempuran Hukum dan Politik dalam Pemberantasan Korupsi
Sepuluh hari lamanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menonaktifkan sementara Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Abdullah Puteh, yang tersangkut kasus dugaan korupsi pembelian helikopter MI-2 buatan Rusia senilai 1,25 juta dolar AS. Akhirnya, pada Senin, 19 Juli 2004, Presiden Megawati memberikan respons. Namun, keputusan yang dikeluarkannya jauh dari harapan KPK. Alih-alih menonaktifkan Puteh seperti yang diminta, Presiden Megawati justru memilih untuk mengalihkan tugas dan wewenang gubernur kepada Wakil Gubernur NAD dan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD). Sikap Presiden ini menunjukkan ketegasan dalam menolak permintaan KPK untuk menonaktifkan Puteh.
Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet, Bambang Kesowo, menjelaskan bahwa instruksi presiden tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU tersebut, penonaktifan seorang gubernur harus melalui mekanisme tertentu, salah satunya adalah rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NAD. Karena rekomendasi tersebut belum dikeluarkan, Presiden Megawati beranggapan bahwa penonaktifan Puteh belum dapat dilakukan. Langkah pengalihan tugas ini, diposisikan sebagai jawaban atas permintaan KPK.
Keputusan Presiden Megawati ini memicu kontroversi besar. Hal ini terutama mengingat pernyataan Megawati sebelumnya saat debat calon presiden, di mana ia menyatakan setuju dengan penonaktifan Puteh jika KPK telah menetapkannya sebagai tersangka dan pejabat pengganti telah ditunjuk. Perbedaan sikap ini menjadi sorotan tajam publik dan kalangan analis politik.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno, dalam beberapa wawancara, menegaskan bahwa pemberhentian seorang gubernur harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Beliau juga berulang kali menekankan perlunya rekomendasi DPRD. Ketidakadaan rekomendasi ini menjadi alasan utama mengapa pemerintah enggan menonaktifkan Puteh.
Namun, polemik semakin memanas karena munculnya argumen mengenai benturan produk hukum. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa permintaan KPK untuk menonaktifkan Puteh berbenturan dengan aturan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf e, secara tegas memberikan wewenang kepada KPK untuk memerintahkan pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Ironisnya, UU tersebut tidak mengatur sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi perintah tersebut. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab Presiden Megawati, sebagai atasan Puteh, enggan memenuhi permintaan KPK.
Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki, menjelaskan dalam jumpa pers bahwa KPK hanya memiliki wewenang untuk meminta penonaktifan. Ia mengakui bahwa penuhi atau tidaknya permintaan tersebut oleh Presiden merupakan ranah politik. Sementara itu, kuasa hukum Abdullah Puteh, Eggy Sudjana, menilai instruksi presiden tersebut tergesa-gesa dan cenderung mengarah pada politisasi kasus, bukan lagi pada penegakan hukum.
Pertanyaan mengenai politisasi dan benturan hukum dalam kasus ini pun mencuat. Namun, Ketua Komisi II DPR Teras Narang dan Wakil Ketua Komisi II DPR Hamdan Zoelva menyangkal adanya benturan hukum. Mereka merujuk pada Pasal 46 ayat 1 UU KPK yang menyatakan bahwa prosedur khusus dalam pemeriksaan tersangka tidak berlaku setelah penetapan tersangka oleh KPK.
Meskipun penjelasan Komisi II DPR yang menggodok UU KPK ini sudah cukup jelas dan berlandasan hukum, polemik tetap berlanjut. Kasus ini semakin menarik karena sulitnya memisahkan aspek hukum dan politik. Mendagri kembali menegaskan bahwa permintaan KPK berada di ranah politik, bukan hukum. Hal ini dibantah oleh Ketua Forum Pemantau KPK, Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa surat KPK kepada Presiden masih berada dalam koridor kewenangan KPK. Romli menekankan bahwa perintah penonaktifan Puteh adalah domain hukum, bukan politik.
Kasus Abdullah Puteh tidak hanya menjadi perhatian para ahli hukum pidana, tetapi juga pakar hukum tata negara dan aktivis LSM. Satya Arinanto (UI) dan Saldi Isra (Universitas Andalas) menyatakan bahwa keengganan Presiden untuk mematuhi perintah KPK merupakan pelanggaran UU KPK dan menunjukkan rendahnya komitmen elite terhadap pemberantasan korupsi. Munarman dari YLBHI bahkan menyatakan bahwa tindakan Presiden dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi.
Kasus ini merupakan ujian awal bagi KPK yang baru dibentuk pada Desember tahun sebelumnya. Keberanian KPK menetapkan Puteh sebagai tersangka jauh lebih cepat dibandingkan Mabes Polri yang masih menjadikan Puteh sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan listrik di Provinsi NAD, meskipun kasus tersebut sudah ditangani jauh lebih lama.
Polemik semakin rumit dengan pengajuan praperadilan oleh Abdullah Puteh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Puteh berargumen bahwa penyidikan KPK tidak sah karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum terbentuk, berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Praktisi hukum Bambang Widjojanto menilai argumen ini inkonsisten, karena gugatan diajukan ke pengadilan negeri, bukan menunggu Pengadilan Tipikor. Ia juga menilai langkah KPK dalam meningkatkan status Puteh menjadi tersangka sebagai langkah yang tepat dan sesuai prosedur.
Argumen menunggu rekomendasi DPRD untuk menonaktifkan gubernur juga dikritik sebagai tidak tepat. Romli Atmasasmita menyerukan agar polemik kewenangan KPK dihentikan dan diserahkan kepada putusan pengadilan yang imparsial. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi adalah masalah hukum, bukan politik, dan tidak dapat dikembalikan pada otoritas politik.
Masalah lain yang muncul adalah belum terbentuknya Pengadilan Tipikor. Meskipun Panitia Seleksi Mahkamah Agung telah mengajukan nama-nama hakim antikorupsi kepada Presiden, Keppres pengangkatan mereka belum juga diterbitkan. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada KPK, tetapi juga pada kinerja Pengadilan Tipikor yang diharapkan segera terbentuk. Jika tidak, pemeriksaan KPK terhadap Puteh akan menghadapi kendala dan menimbulkan ketidakjelasan.
Kasus Abdullah Puteh mengungkapkan realitas kompleks pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana hukum dan politik seringkali bercampur aduk, menciptakan hambatan dalam penegakan hukum dan keadilan. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah pemberantasan korupsi di Indonesia benar-benar serius dan konsisten?
**Kata Kunci:** Abdullah Puteh, KPK, Presiden Megawati, Korupsi, Pengadilan Tipikor, Pemerintahan Daerah, Aceh, Hukum, Politik, Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Praperadilan.